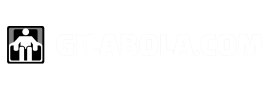Sunderland akhirnya kembali berdiri sejajar dengan elite sepak bola Inggris setelah hampir satu dekade dilanda kemerosotan. Klub berjuluk The Black Cats itu menutup perjalanan panjang penuh gejolak dengan kepastian kembali ke Premier League, sekaligus membuka babak baru yang jauh lebih ambisius. Tidak sekadar bertahan, Sunderland kini bahkan berani membayangkan tampil di kompetisi Eropa.
Belanja musim panas lebih dari 150 juta pound atau sekitar Rp3 triliun menjadi penegasan bahwa Sunderland tidak ingin bernasib sebagai tim promosi yang hanya singgah semusim. Sejumlah kemenangan awal musim, termasuk gol penentuan di masa tambahan waktu di markas Chelsea, memberi sinyal kuat bahwa skuad muda asuhan Regis Le Bris mampu bersaing lebih dari sekadar zona aman.
Memasuki sepertiga akhir musim, Sunderland tercatat hanya menghabiskan sekitar sepuluh pekan di luar posisi Eropa. Sebuah pencapaian langka bagi tim promosi, mengingat sepanjang sejarah Premier League hanya empat tim promosi yang mampu menembus zona tersebut. Dulu, bertahan hidup adalah batas tertinggi ambisi mereka. Kini, sepuluh tahun setelah awal kejatuhan itu, Sunderland mulai berani bermimpi lebih jauh.
Awal Kemerosotan di Premier League
Kemunduran Sunderland sebenarnya sudah terasa jauh sebelum mereka terdegradasi. Selama satu dekade bertahan di Premier League, klub ini kerap hidup dalam siklus selamat di detik terakhir, solusi jangka pendek, dan pergantian pelatih yang terlalu sering. Rata-rata posisi akhir mereka berada di peringkat 15, dengan pencapaian terbaik finis ke-10 di bawah Steve Bruce.
Skuad dibangun tanpa nilai jual jangka panjang. Ketika Sam Allardyce datang pada musim 2015/16, situasi krisis sudah menjadi kebiasaan. Sunderland selamat dengan selisih dua poin, namun akar masalah tidak pernah tersentuh. Musim berikutnya, David Moyes mewarisi tim hasil kebijakan jangka pendek dan hasil akhirnya sesuai dugaan banyak pihak: degradasi. Turun kasta terasa bukan sebagai kejutan, melainkan konsekuensi logis dari bertahun-tahun berjalan di tepi jurang.
Dua Kali Turun Kasta dan Kehilangan Arah
Jika degradasi ke Championship terbilang dapat diprediksi, kehancuran berikutnya justru jauh lebih mengejutkan. Sunderland berharap segera kembali ke Premier League, namun justru terjun bebas ke League One. Simon Grayson hanya bertahan beberapa bulan, Chris Coleman datang tanpa dukungan finansial memadai, dan ruang ganti yang terpecah membuat klub kembali terdegradasi.
Pemilik saat itu, Ellis Short, melunasi utang klub sebelum melepas kepemilikan kepada Stewart Donald. Serial dokumenter Sunderland ‘Til I Die memperlihatkan kekacauan tersebut, tetapi realitasnya lebih suram. Sunderland kehilangan identitas, arah, dan keyakinan.
League One tidak serta-merta memulihkan Sunderland, justru membuka luka yang lebih dalam. Jack Ross ditunjuk sebagai pelatih, namun optimisme tetap terbatas. Dua kali mencapai Wembley pada musim 2018/19 berakhir dengan kekecewaan: kalah adu penalti di final EFL Trophy melawan Portsmouth dan kebobolan di menit akhir final play-off kontra Charlton.
Kegagalan berulang membebani skuad muda yang harus matang lebih cepat di bawah tekanan suporter yang gelisah. Sunderland terasa seperti klub besar dengan hasil ala klub kecil. Masalah keuangan dan stagnasi memperlebar jarak antara pendukung dan pemilik.
Pada Februari 2021, Kyril Louis-Dreyfus yang berusia 23 tahun mengambil alih saham mayoritas dan menjadi ketua klub termuda dalam sejarah sepak bola Inggris. Kehadirannya membawa kejelasan yang lama hilang. Sunderland menjuarai EFL Trophy sebulan kemudian di bawah Lee Johnson, meski momentum itu tidak bertahan lama. Kekalahan 0-6 dari Bolton pada Desember berikutnya mengakhiri masa Johnson.
Keputusan Louis-Dreyfus menunjuk Alex Neil menjadi titik balik. Neil mencatatkan 17 laga tanpa kekalahan dan mengantar Sunderland menang 2-0 atas Wycombe di final play-off 2022. Setelah empat tahun terjebak, Sunderland akhirnya keluar dari League One.
Tumbuh di Championship dan Jalan Kembali
Alex Neil sempat memperpanjang kontrak pada Agustus 2022, namun hanya beberapa pekan kemudian hengkang ke Stoke City, mengejutkan banyak pihak yang berharap ia menjadi fondasi stabilitas baru. Tony Mowbray menggantikannya dan membawa Sunderland finis di peringkat enam serta melaju ke semifinal play-off, sebelum disingkirkan Luton Town.
Musim 2023/24 berjalan kacau. Mowbray diberhentikan, Michael Beale hanya bertahan 63 hari, rekor terpendek dalam sejarah klub, dan Mike Dodds sebagai pelatih interim mengawasi kemerosotan hingga finis di posisi 16.
Harapan baru datang pada Juli 2024 saat Regis Le Bris ditunjuk, meski reputasinya sempat dipertanyakan setelah terdegradasi bersama Lorient. Namun Sunderland melihat Le Bris sebagai sosok yang tepat untuk mewujudkan model rekrutmen berbasis data. Fokus pada pemain di bawah usia 24 tahun, kepercayaan pada talenta muda, dan identitas permainan yang jelas langsung terasa.
Agustus tanpa kekalahan mengubah atmosfer. Sunderland bertahan di papan atas, mengamankan tiket play-off, menyingkirkan Coventry, dan menghadapi Sheffield United di Wembley. Sempat tertinggal hampir sepanjang laga final, gol penyeimbang Mayenda membuka jalan sebelum pemain akademi, Tommy Watson, mencetak gol kemenangan di masa tambahan waktu. Sebuah momen yang akan dikenang selamanya di Wearside.
Dari Bertahan Hidup ke Ambisi Baru
Perjalanan Sunderland selama satu dekade dipenuhi ekstrem: sakitnya degradasi beruntun, kesabaran panjang di League One, dan loyalitas suporter yang menolak membiarkan klubnya tenggelam dalam ketidakrelevanan. Klub ini membuktikan bahwa ketahanan dan arah yang jelas mampu membangun kembali identitas.
Kisah yang dulu tentang bertahan hidup kini berubah menjadi cerita tentang ambisi. Setelah bertahun-tahun berjuang, Sunderland tidak lagi takut menghadapi masa depan. Mereka mulai berani bermimpi menembus Eropa.
Biar nggak ketinggalan update terkini, yuk follow kami di Google News di sini!